Gunung Merapi bukan sekadar simbol geografis bagi Yogyakarta, melainkan menjadi representasi alam yang hidup menyatu, berdetak, dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya. Ia adalah sosok yang disakralkan sekaligus diwaspadai, menjadi sumber penghidupan melalui tanah yang subur, namun juga menyimpan potensi bencana yang mematikan. Dalam imajinasi kolektif masyarakat Jawa, Merapi bukanlah benda mati, melainkan entitas yang memiliki kehendak dan dinamika tersendiri. Pandangan ini tercermin dalam berbagai tradisi lokal, seperti upacara Labuhan Merapi, yang menunjukkan hubungan spiritual antara manusia dan gunung. Merapi, sebagai salah satu gunung api paling aktif di dunia, tidak hanya menghadirkan potensi bencana, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membentuk adaptasi masyarakat terhadap dinamika lingkungan yang berubah, termasuk perubahan iklim global.
Salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Merapi dan kebencanaan Indonesia terjadi pada tahun 2010, ketika gunung ini mengalami letusan dahsyat yang melampaui skenario terburuk yang diprediksi sebelumnya. Letusan ini menghasilkan kolom erupsi mencapai lebih dari 17 km dan memuntahkan awan panas sejauh 15 km ke berbagai arah lereng, menjangkau desa-desa yang selama ini dianggap cukup aman. Lebih dari 350 jiwa melayang, termasuk tokoh spiritual juru kunci Merapi, Mbah Maridjan, yang menjadi simbol keteguhan dan kedekatan spiritual masyarakat dengan gunung. dan memaksa puluhan ribu lainnya mengungsi (BNPB, 2011). Abu vulkanik yang menyebar hingga Jawa Barat dan Kalimantan turut memengaruhi pola cuaca lokal dalam jangka pendek.
Fenomena iklim yang terdampak akibat letusan Merapi menunjukkan keterkaitan erat antara aktivitas geologis dan dinamika atmosfer lokal. Salah satu dampak yang paling nyata pasca letusan besar adalah terjadinya penurunan suhu udara di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut laporan BMKG (2010), suhu di sekitar Yogyakarta sempat menurun sekitar 1 hingga 2°C selama beberapa minggu setelah letusan yang disertai gangguan sinar matahari langsung. Selain itu, langit yang tertutup oleh lapisan abu dan partikel halus menyebabkan gangguan terhadap fotosintesis tanaman, memperlambat pertumbuhan vegetasi dan menurunkan hasil panen di beberapa daerah pertanian sekitar.

(Sumber: Abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi menutupi sebuah desa di Muntilan, Jawa Tengah, Indonesia, Minggu, 7 Nov 2010. (AP Photo/Trisnadi))
Namun ada yang menarik, yaitu bagaimana masyarakat lereng Merapi beradaptasi dengan siklus letusan yang semakin sulit diprediksi karena faktor perubahan iklim. Perubahan musim hujan dan kemarau, juga disertai anomali suhu global, memengaruhi tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap erupsi. Masyarakat kini hidup dalam situasi di mana perubahan iklim memperumit prediksi vulkanik yang dulu lebih mudah dibaca secara lokal. Masyarakat di sekitar lereng Merapi, khususnya di wilayah seperti Cangkringan dan Kemalang, merespon situasi tersebut dengan mulai memodifikasi sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal dengan pendekatan ilmiah. Sirine peringatan, jalur evakuasi, dan simulasi bencana secara berkala kini dilakukan lebih rutin dan terstruktur, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat bahwa terdapat sekitar 74 desa rawan bencana kini memiliki sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat. Hal ini merupakan bentuk adaptasi yang menggabungkan pemahaman akan perubahan iklim dan dinamika Merapi secara bersamaa, menciptakan semecam “ketahanan iklim lokal.” Akan tetapi, tidak hanya pada level kebencanaan, perubahan iklim juga berdampak langsung pada sektor pertanian yang menjadi tumpuan banyak warga sekitar Merapi. Siklus tanam yang terganggu akibat pergeseran musim serta hujan asam dari abu vulkanik menyebabkan penurunan hasil panen. Laporan dari Dinas Pertanian DIY tahun 2021 mencatat penurunan hasil panen cabai dan tomat sebesar 28% dibanding tahun sebelumnya, terutama di kawasan Kaliurang dan Pakem.
Beberapa petani mulai beralih ke sistem pertanian tumpangsari dan rumah kaca sederhana yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem pasca letusan Merapi. Selain itu, program edukasi tentang pertanian berkelanjutan mulai diterapkan oleh kelompok tani di lereng Merapi, bekerja sama dengan universitas lokal seperti UGM dan UII. Selain di aspek pertanian, aspek sosial pun tidak luput dari pengaruh letusan Merapi dan perubahan iklim. Masyarakat yang tinggal di pengungsian atau mengalami relokasi permanen, mereka beberapa mengalami tekanan psikologis dan sosial. Namun, melalui pendekatan komunitas, ritual budaya seperti Labuhan Merapi serta gotong royong menjadi fondasi kuat dalam proses pemulihan dan adapatsi sosial.
Pada tingkat kebijakan, Pemerintah DIY telah memasukkan aspek perubahan iklim ke dalam rencana penanggulangan bencana tahunan. Termasuk diantaranya upaya reboisasi, konservasi mata air, dan penguatan desa tangguh bencana (Desatana) sebegai ujung tombak ketahanan lokal. Keselurugan dinamika ini menunjukka bahwa di bawah bayang-bayang Gunung Merapi, masyarakat Yogyakarta tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi. Mereka membuktikan bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim tidak melulu mengenai teknologi tinggi, tetapi juga soal kolaborasi, kearifan lokal, dan kemauan belajar dari bencana.
Merapi akan terus menyala dan dunia akan terus berubah. Namun, selama masyarakatnya terus bergerak, belajar, dan bersiap, maka mereka akan selalu menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan alam, seberbahaya apa pun ia terlihat.

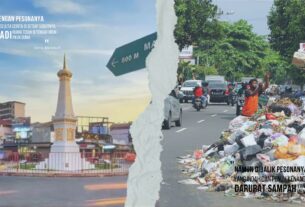


Wah tulisannya keren banget! Nggak cuma informatif, tapi juga terasa dekat sama kehidupan sehari-hari warga Jogja. Salut sama bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan bijak, memadukan kearifan lokal dan ilmu modern. Merapi memang “hidup”, dan masyarakatnya pun ikut terus belajar dan bertumbuh